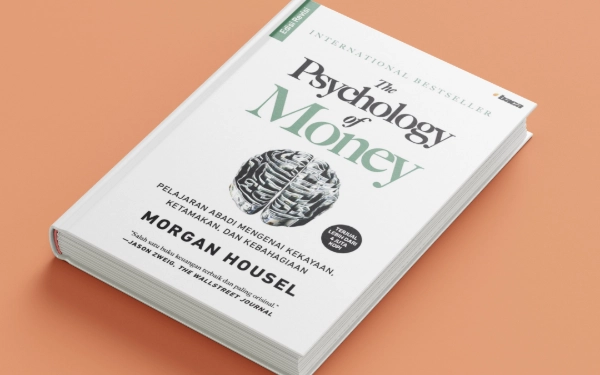KETIK, SURABAYA – “Apabila saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikan Indonesia Merdea. Saya tidak ingin dikubur di Makam Pahlawan (Kalibata). Saya ingin dikuburkan di tempat kuburan rakyat biasa yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya (Mohammad Hatta, 1975).”
Revisi UU TNI meletupkan kekhawatiran masyarakat akan dihidupkannya kembali dwi fungsi ABRI seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Meski hal ini terus dibantah pemerintah dan TNI, kekhawatiran itu tetap memantik demo besar-besaran yang kemungkinan masih akan berlangsung usai lebaran.
Selain revisi UU TNI, sorotan lain adalah keberadaan banyaknya perwira TNI yang kini menduduki atau rangkap jabatan di badan usaha milik negara atau BUMN. Salah satunya yang paling mencolok adalah penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Perum Bulog. Saat ditunjuk pada 8 Februari 2025 lalu, Novi masih menjabat sebagai Danjen Akademi TNI.
Dalam sejumlah kesempatan, pemerintah beralasan memberikan jatah jabatan strategis BUMN kepada perwira TNI karena mereka dianggap memiliki kapasitas untuk memimpin perusahaan milik negara tersebut.
Namun fakta sejarah menunjukkan, penunjukkan perwira militer untuk mengisi jabatan strategis di BUMN kerap kali berujung masalah. Salah satu yang menonjol adalah penunjukan perwira militer untuk memimpin Perusahaan Minyak Negara (Permina, sekarang disebut Pertamina) di masa awal Orde Baru berkuasa.
Mayjen Ibnu Sutowo pertama kali ditunjuk menjadi Direktur Permina pada tahun 1957, seiring dengan gagasan Jenderal Abdul Haris Nasution dengan Dwi Fungsi ABRI yang menginginkan agar prajurit aktif juga mengisi jabatan strategis di sipil. Lalu, saat Soeharto mulai menjadi presiden, Ibnu Sutowo yang kemudian naik pangkat menjadi Letjen, kembali ditunjuk menjadi Dirut Pertamina pada tahun 1968.
Ibnu Sutowo memimpin Pertamina dengan membawa serta sejumlah orang kepercayaannya dari militer, salah satunya adalah Letkol Achmad Thahir yang kemudian dipercaya menjadi asistem umum Dirut Pertamina.
Selama memimpin Pertamina, kedua perwira militer aktif ini dikenal doyan hidup mewah, jauh melampaui kelaziman gaji resminya. Termasuk Thahir yang selain berfoya-foya, juga gemar main perempuan.
Gaya hidup mewah kedua perwira militer itu selama memimpin BUMN sebenarnya sudah memancing kecurigaan dari beberapa pers yang masih memiliki jiwa kritis.
Kebebasan Ibnu Sutowo dan Achmad Thahir untuk merampok uang rakyat di Pertamina itu juga ditopang dengan model kelembagaan BUMN tersebut. Saat itu, Pertamina bisa bergerak bebas tanpa ada pengawasan dari pemerintah (Bappenas) dan juga DPR, serta tanpa ada audit yang ketat. Agak mirip dengan sistem yang berlaku untuk Danantara di era Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Barulah 6 tahun kemudian, perilaku lancung keduanya mulai terendus ke Presiden Soeharto. Sebelumnya, Soeharto yang merupakan kolega Ibnu Sutowo semasa perang kemerdekaan, selalu tak mempercayai bisikan atau laporan media perihal perilaku korup dan gaya hidup mewah Ibnu Sutowo dan Achmad Thahir.
Dibentuklah tim khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pertamina. Mantan Wapres Mohammad Hatta yang saat itu sudah menjadi rakyat biasa, diminta untuk menjadi penasehat di tim tersebut.
Belakangan terungkap, Pertamina terbelit utang akibat salah kelola hingga mencapai USD 10,5 Miliar. Jumlah yang sangat fantastis di tahun 1975. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, Pertamina baru saja menikmati lonjakan harga minyak dunia pada awal tahun 1970-an. Jika dikelola dengan benar, mungkin saja Indonesia saat itu menjadi negara kaya seperti negara minyak lainnya.
Meski terang benderang melakukan praktik korup hingga ratusan milyaran rupiah saat itu, baik Ibnu Sutowo maupun Achmad Thahir tak pernah diseret ke meja hijau. Hartanya juga tak disita negara. Keduanya mewariskan kekayaan tak terhingga kepada anak cucu, seolah seperti tak habis dimakan tujuh turunan.
Bahkan Achmad Thahir yang menyimpan ratusan juta dolar uang hasil korupsinya melalui istri mudanya, saat meninggal tahun 1976, justru dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Pertimbangan pemerintah saat itu, adalah karena Achmad Thahir merupakan tentara yang pernah ikut terlibat dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Kegusaran Bung Hatta dan Cara Halusnya Mengkritik Penguasa
Bung Hatta yang menjadi penasehat dalam tim khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pertamina era Ibnu Sutowo, tahu betul bagaimana uang negara dirampok oleh para perwira militer aktif tersebut.
Sosok penggila buku yang dikenal berintegritas dan bersahaja itu suatu ketika menulis surat wasiat, tertanggal 10 Februari 1975. Ia menginginkan agar tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, tetapi di pekuburan umum biasa.
Alasannya, karena “Saya ingin dikuburkan di tempat kuburan rakyat biasa yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya,” tulis Bung Hatta dalam surat wasiat yang versi aslinya diunggah oleh sang cucu, Gustika Hatta lewat akun twitter (sekarang X) pada 31 Maret 2020.
Namun, belakangan terungkap, ada alasan lain yang menyebabkan Bung Hatta menolak dimakamkan di TMP Kalibata. Salah satu putri Bung Hatta, Meutia Hatta dalam sebuah diskusi di tahun 2017 mengungkap alasan spesifik sang ayah menolak dimakamkan di TMP Kalibata, pemakaman khusus orang-orang terhormat.
“Saya tidak mau di sana, karena ada orang bersalah tapi dimakamkan di sana (TMP Kalibata),” ujar Meutia Hatta menirukan ucapan sang ayah saat masih hidup.
Bung Hatta memang tidak menyebut nama siapa ‘orang bersalah’ yang ia maksud.
Menurut ekonom senior Faisal Basri, itu merupakan cara halus Bung Hatta untuk memprotes dua hal kepada rezim Soeharto. Yakni pembiaran atas kasus mega korupsi Pertamina, serta dimakamkannya Achmad Thahir di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.
Sikap Hatta yang menolak dimakamkan di TMP Kalibata karena ada koruptor perwira TNI itu, juga diikuti oleh koleganya sesama aktivis Petisi 50, Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Iman Santoso.
Ia tak sudi dimakamkan bersama koruptor di TMP Kalibata. “Ah, nanti para koruptor menegur saya. Padahal saya mau istirahat,” tutur Hoegeng dalam salah satu wawancara yang diterbitkan di Majalah Forum Keadilan edisi 19 Agustus 1993. (*)