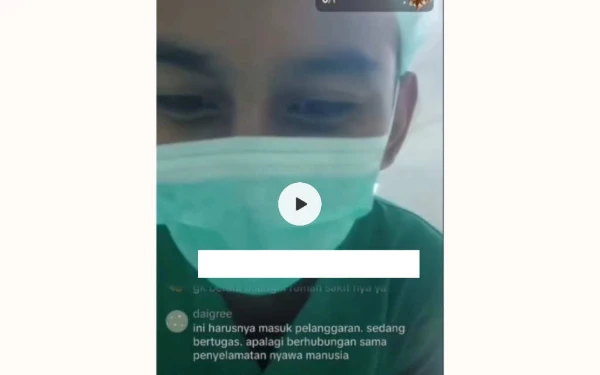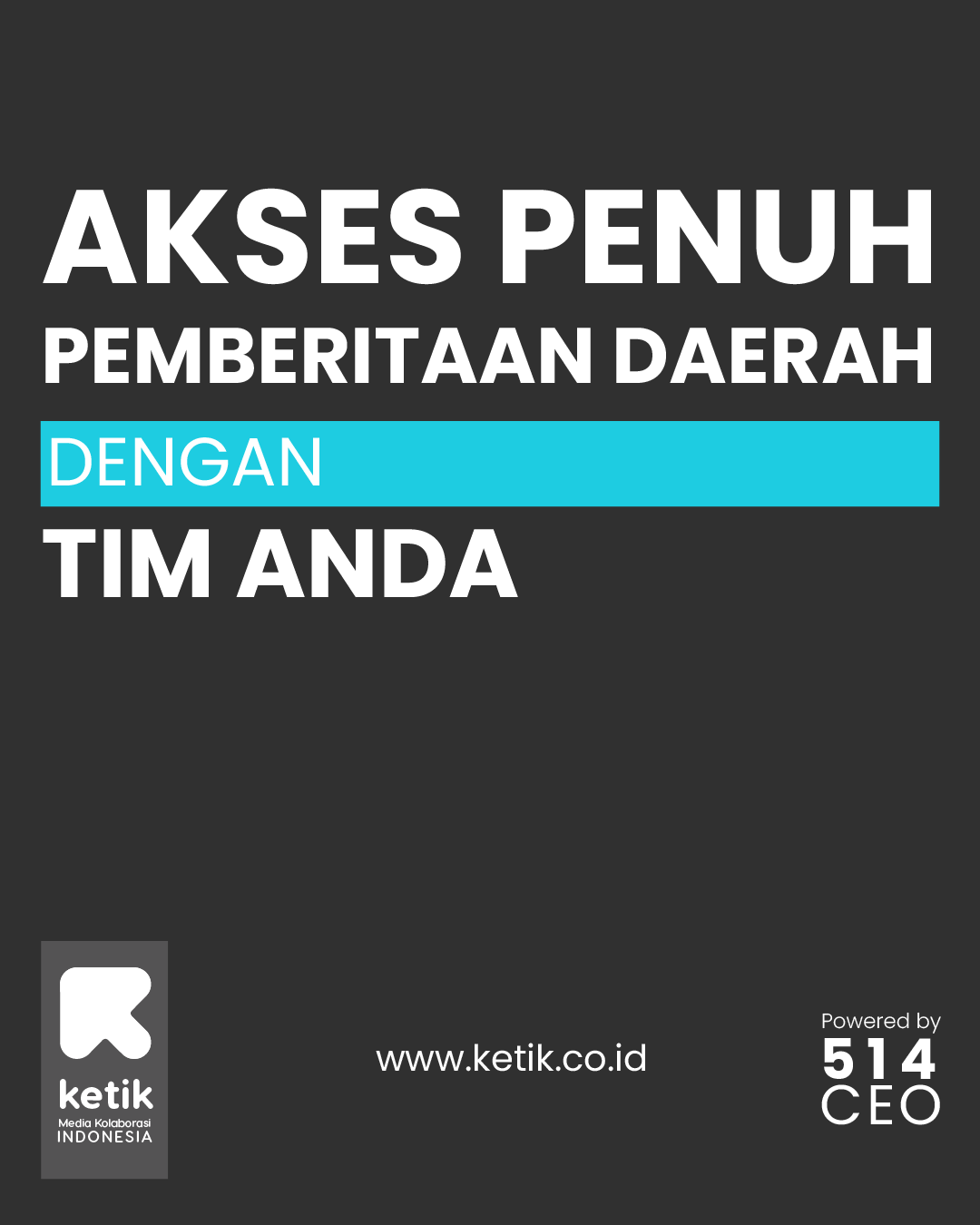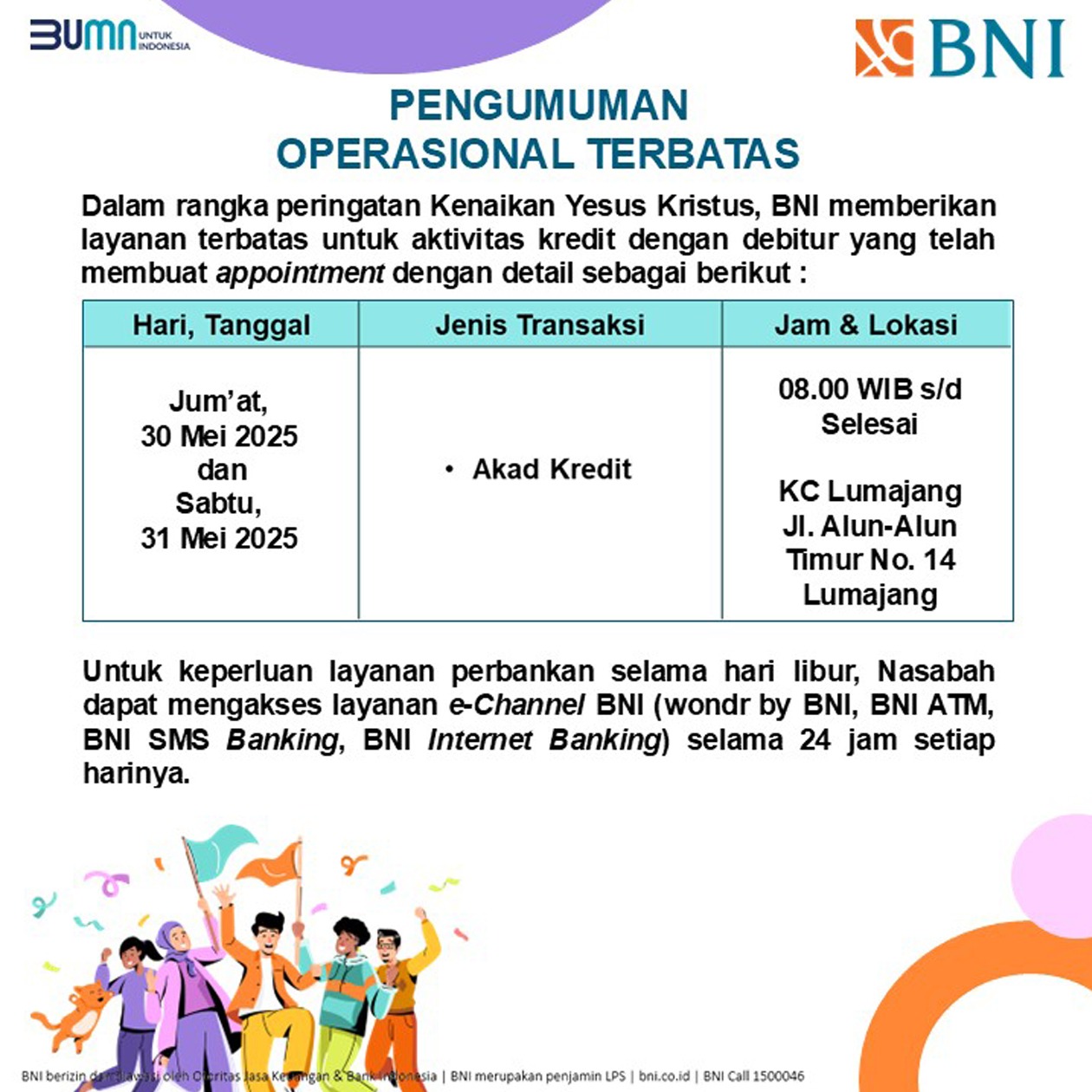Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, kembali mencatatkan angka positif pada Februari 2025. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,61 persen, turun 0,13 persen dibandingkan Februari 2024.
Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami peningkatan signifikan menjadi 74,25 persen, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 24,76 juta orang. Capaian ini sekilas menunjukkan perbaikan dalam iklim ketenagakerjaan, namun di balik angka-angka ini tersimpan tantangan besar yang harus dihadapi.
Peningkatan jumlah penduduk bekerja sebanyak 628,62 ribu orang dalam setahun terakhir menandakan bahwa peluang kerja di Jawa Timur mulai terbuka. Sektor-sektor seperti pengangkutan dan pergudangan, akomodasi dan penyediaan makan minum, serta aktivitas kesehatan mengalami pertumbuhan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.
Namun, struktur pasar tenaga kerja di Jawa Timur masih didominasi oleh sektor informal, yang mencapai 63,91 persen, sementara pekerja formal hanya 36,09 persen, menurun dari tahun sebelumnya. Dominasi pekerja informal menjadi potret nyata lemahnya perlindungan sosial dan rendahnya kualitas pekerjaan.
Pekerja informal, yang sebagian besar berada di sektor pertanian, perdagangan kecil, dan jasa lainnya, rentan terhadap guncangan ekonomi dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap jaminan sosial. Hal ini berdampak langsung pada kerentanan rumah tangga miskin, yang sebagian besar menggantungkan hidup pada pekerjaan informal berpenghasilan rendah. Tanpa adanya upaya transformasi struktural, ketimpangan dan kemiskinan di Jawa Timur akan terus berlanjut.
Lebih memprihatinkan lagi, tingkat pengangguran tertinggi tercatat pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 5,87 persen dan lulusan universitas sebesar 5,60 persen. Angka ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan pasar kerja (skill mismatch).
Lulusan yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian justru banyak yang terjebak dalam pengangguran atau pekerjaan di luar bidang keahlian mereka. Ini menjadi indikasi bahwa sistem pendidikan, khususnya vokasi, perlu segera direformasi agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar.
Lebih memprihatinkan, TPAK perempuan yang meningkat menjadi 62,81 persen mayoritas diserap ke sektor informal dan paruh waktu. Tanpa kebijakan yang responsif gender dan berbasis perlindungan sosial, maka perempuan akan semakin rentan terhadap kemiskinan.
Di sisi lain, ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan semakin tajam. Meski TPT perkotaan turun menjadi 3,76 persen, TPT perdesaan justru meningkat menjadi 3,40 persen, memperlihatkan kesenjangan pembangunan ekonomi antarwilayah.
Banyak penelitian yang bisa dijadikan landasan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut, salah satunya terbaru oleh Christiayu Natalia (2024) dari Universitas Brawijaya menekankan pentingnya memahami transisi pekerja blue-collar dalam dinamika pasar kerja Indonesia.
Penelitian ini menemukan bahwa pekerja blue-collar—yang didominasi oleh tenaga kerja dengan keterampilan rendah di sektor-sektor seperti pertanian, pengolahan, dan jasa informal—menghadapi tantangan besar dalam bertransisi ke pekerjaan yang lebih stabil dan bernilai tambah.
Penelitian ini menyarankan bahwa penguatan modal manusia (human capital), peningkatan akses pelatihan kerja berkualitas, dan peningkatan digitalisasi serta infrastruktur di wilayah menjadi kunci untuk mempercepat transisi pekerja ke sektor formal yang lebih produktif.
Temuan ini relevan untuk Jawa Timur, di mana dominasi pekerja informal dan rendahnya proporsi pekerja berpendidikan tinggi mencerminkan perlunya kebijakan yang mendukung transisi tenaga kerja secara inklusif.
Selain itu, studi oleh Pratomo (2022) mengungkapkan bahwa di Indonesia, pekerja blue-collar usia muda sangat rentan bertransisi menjadi NEET (Not in Education, Employment, or Training), terutama akibat dampak pandemi dan kurangnya akses terhadap pendidikan vokasional dan pelatihan.
Hal ini menguatkan pentingnya investasi besar-besaran pada pendidikan vokasi dan program pelatihan berbasis kompetensi untuk menyiapkan angkatan kerja muda yang tangguh.
Penerapan kebijakan berbasis riset seperti yang diajukan Christiayu (2024) dan Pratomo (2022) akan memperkuat transformasi struktural Jawa Timur, dari dominasi sektor informal dan padat karya menjadi sektor modern yang berbasis teknologi dan industri bernilai tambah.
Reformasi pendidikan vokasi, seperti penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, pengembangan pelatihan berbasis kompetensi, serta insentif untuk pengusaha dan pekerja muda, sangat penting untuk menurunkan mismatch keterampilan.
Program-program inklusi keuangan dan perlindungan sosial bagi pekerja informal dan perempuan harus diperkuat untuk mendorong kestabilan ekonomi rumah tangga.
Selain itu, kebijakan yang fokus pada perdesaan dengan memperkuat akses modal, pelatihan kerja, dan digitalisasi akan menurunkan TPT perdesaan dan mengurangi migrasi paksa ke perkotaan. Hal ini sejalan dengan temuan Christiayu yang menekankan pentingnya faktor karakteristik kewilayahan, seperti digitalisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, dalam mempengaruhi transisi pekerja blue-collar.
Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya faktor karakteristik kewilayahan, seperti digitalisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, dalam mempengaruhi transisi pekerja blue-collar. Ini harus direspon dengan program inklusi digital yang massif, peningkatan produktivitas sektor pertanian, dan penguatan UMKM berbasis desa.
Pada akhirnya, transformasi ketenagakerjaan di Jawa Timur harus melampaui angka-angka statistik. Kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, dan keadilan sosial harus menjadi indikator utama.
Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi model pengembangan ekonomi inklusif di Indonesia, tetapi ini hanya akan terwujud dengan keberanian untuk berinovasi, berkolaborasi lintas sektor, dan menempatkan kesejahteraan manusia sebagai pusat pembangunan. Saatnya Jawa Timur tidak hanya sekadar tumbuh, tetapi tumbuh dengan kokoh, adil, dan berkelanjutan.
*) Ahmad Syaifullah adalah Alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB) X, Pegiat di Social and Economic Center (SEC), sekaligus Dewan Instruktur PC GP Ansor Kota Kraksaan
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email [email protected].
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan ide
- ntitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)