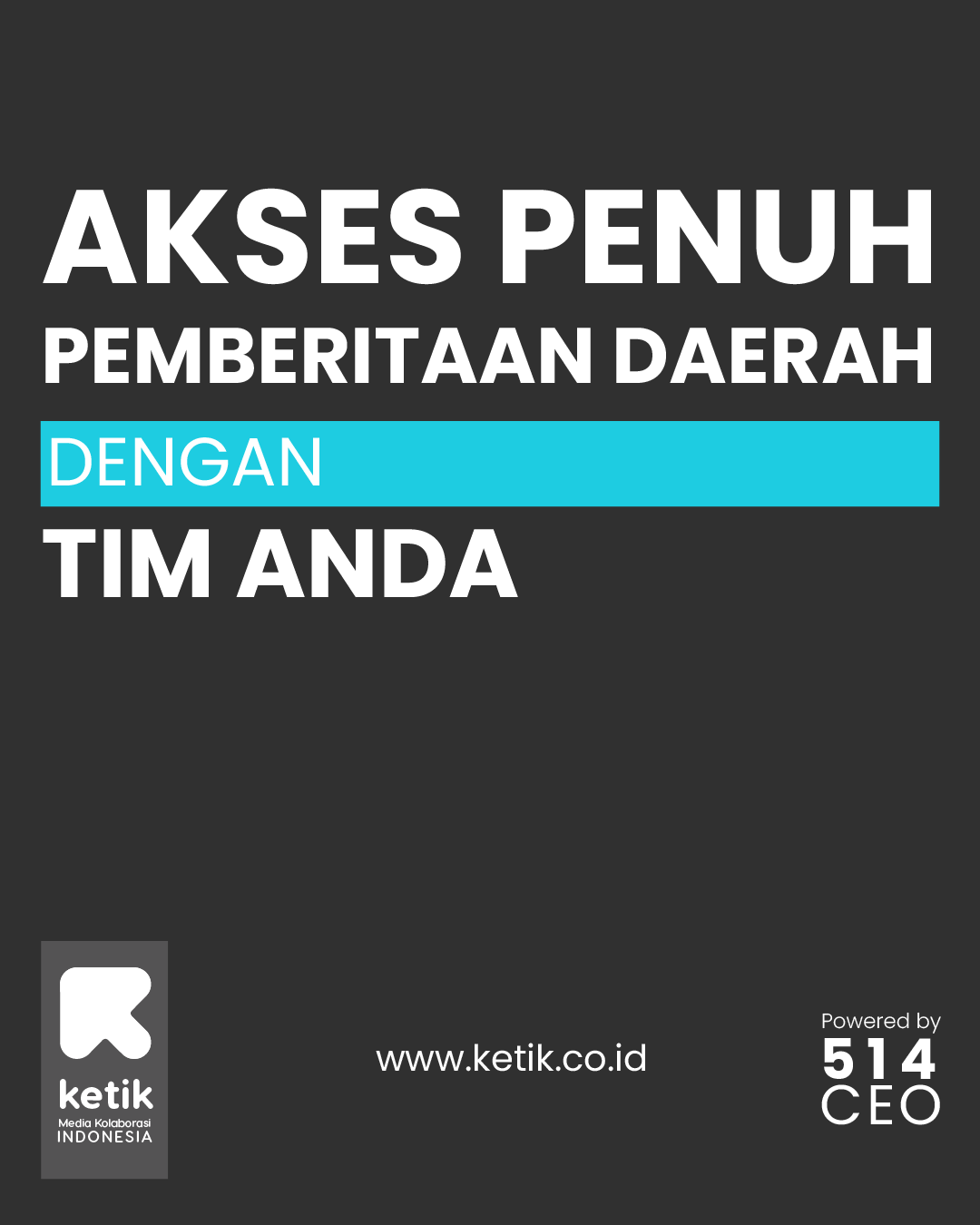Demokrasi Indonesia, yang telah dibangun sejak jatuhnya rezim otoriter Soeharto pada 1998, kini menghadapi ujian besar dengan disahkannya RUU TNI. RUU baru ini mengizinkan kembali perwira militer aktif mengisi beberapa jabatan sipil tanpa pensiun.
Berbeda dari gagasan dan amanat reformasi yang membatasi militer untuk berfokus pada pertahanan, menghapus pengaruh besar militer dalam pemerintahan. Di tengah perubahan ekonomi pasca covid-19. Dengan kebijakan penghematan ketat, pengangguran meningkat dan deflasi yang terus berlangsung, RUU ini memicu pertaruhan tentang risiko demokrasi dan akan memperburuk ekonomi.
Dalam bukunya Corona Crash (2020), Grace Blakeley menuliskan tentang perubahan yang akan terjadi pasca pandemi Covid-19. Alih-alih tetap mempertahankan sistem yang demokratis dalam masa pemulihan, Grace melihat bahaya dari hutang yang diambil negara sebagai pemulihan ekonomi akan mengakibatkan kebijakan pengetatan anggaran dan menciptakan lingkaran setan: austerity melemahkan ekonomi, keresahan bertambah, dan kekuatan militer meluas, merusak demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dasar dari argumen ini adalah negara-negara telah menghabiskan lebih banyak pengeluaran karena banyak perusahaan besar perlu diselamatkan. Kita melihat dinamika yang sama setelah pandemi dan fase pemulihan ekonomi di hampir seluruh dunia.
Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan; bail-out pada banyak perusahaan besar, penghematan anggaran dengan penyesuaian fiskal dan untuk mengamankan kepentingan negara, militer digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas.
Saat pandemi dengan dalih penegakan disiplin sosial, TNI diberi kewenangan leluasa mengakomodasi pasukannya hingga ke tingkat desa, mengembalikan struktur komando teritorial yang semenjak reformasi perannya tidak lagi relevan.
Penggunaan secara masif struktur komando TNI untuk melakukan pendisiplinan publik berlanjut dilakukan Presiden Joko Widodo atas nama pemulihan ekonomi. Kedok kesehatan dan ekonomi ini telah menjadikan TNI seolah kebal dari pengawasan sipil.
Peranan TNI dalam ranah sipil semakin meningkat pada era Prabowo. Presiden dengan latar belakang militer ini mendayagunakan struktur komando Angkatan Darat untuk menjalankan program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembukaan lahan pertanian dan penyerapan dan pengawasan gabah petani.
Beberapa jabatan sipil telah diganti militer aktif, hingga pada puncaknya adalah pengesahan revisi UU TNI. Memberikan legitimasi bagi TNI untuk semakin memasuki ruang sipil. RUU baru ini berpotensi mengembalikan pola lama doktrin dwifungsi era Orde Baru.
Persoalan ekonomi saat ini sangat dapat kita curigai menjadi latar belakang kemunculan dan pengesahan yang seolah tergesa-gesa dalam RUU ini. Peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo telah juga mewarisi kebijakan-kebijakan yang berdampak panjang. Prabowo kini dihadapkan dengan warisan pertumbuhan ekonomi yang melambat, fondasi ekonomi yang keropos, ketimpangan ekonomi yang makin buruk.
Terbukti pada empat bulan menjabat, PHK besar-besaran terjadi di sektor formal dengan peningkatan sebesar 20,2 persen, sektor informal yang menyumbang 53 persen tenaga kerja produktivitasnya menurun dengan kelas menengah menjadi turun kelas, sementara kebijakan penghematan pemerintahan telah berdampak pada layanan sosial dan infrastruktur. Deflasi yang terus berlanjut di angka 0,48 persen (mtm) memperparah stagnasi ekonomi, mendorong pemerintah mencari solusi cepat.
Di tengah situasi seperti ini, pemerintah tampaknya memandang militer sebagai alat untuk mengamankan stabilitas kepentingan. Dengan risiko protes akibat pengangguran dan pemotongan subsidi yang mungkin terjadi, militer diharapkan dapat menegakkan kebijakan sulit, seperti yang terjadi pada krisis 1997–1998. Namun, langkah ini justru bisa memperdalam ketidakstabilan ekonomi jangka panjang serta memberikan resiko yang lebih buruk terhadap demokrasi.
Risiko Demokrasi: Merusak Institusi Inklusif
Melalui revisi UU TNI, risiko terhadap demokrasi telah menjadi sorotan utama. Dalam demokrasi, militer seharusnya berada pada kontrol sipil. Militer tidak dapat bertindak sewenang-wenang tanpa melalui komando pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa militer dalam negara demokrasi dibutuhkan sebagai tuntutan pertahanan untuk menciptakan kedamaian.
Keterlibatan militer diluar tuntutan pertahanan hanya akan mengaburkan ranah militer-sipil dan dapat memusatkan kekuasaan dan melemahkan akuntabilitas. Secara lebih jauh, hubungan kabur militer-sipil ini justru menciptakan institusi ekstraktif yang menguntungkan elit.
Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail (2012) menjelaskan bahwa institusi ekstraktif lahir dari otoritarianisme sehingga melahirkan monopoli, kebalikan dari institusi inklusif yang memastikan partisipasi luas dan kontrol atas kekuasaan sebagai kunci kemakmuran ekonomi.
Olehnya, keterlibatan militer dalam pemerintahan hanya akan menciptakan institusi ekstraktif yang menguntungkan elit, menghambat inovasi dan investasi pada masyarakat. Kemajuan demokrasi Indonesia sejak 1998 yang telah ditandai bergantung pada inklusivitas ini, kini terancam oleh UU tersebut. Pengaburan peran militer dan sipil bisa menurunkan kualitas institusi, membuka peluang korupsi dan inefisiensi.
Dampak Ekonomi: Inefisiensi, Deflasi, dan Ketimpangan
Dalam upaya mewujudkan mimpi 8 persen pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo, revisi UU TNI bisa sangat mungkin malah menggagalkan cita-cita tersebut. Paul Collier dalam The Bottom Billion (2008) menjelaskan dampak peran militer dalam ruang sipil terhadap institusi ekonomi yang ia sebut sebagai kerapuhan negara. Ia menunjukkan bahwa negara dengan institusi rapuh dan tekanan ekonomi rentan sangat mungkin beralih ke otoritarianisme atau dominasi militer.
Kombinasi pengangguran, deflasi, dan ketegangan institusional di Indonesia pada hari ini setidaknya mencerminkan hal tersebut. Tuntutan pertumbuhan ekonomi serta kepentingan pemodal menciptakan ancaman semu, dimana negara mesti memastikan bahwa sumber pendanaan ini harus terus berjalan tanpa hambatan, ancaman, ataupun gangguan yang membuatnya berhenti.
Melalui ancaman semu inilah celah militer masuk dalam ruang spil menjadi terbuka. Tetapi, Collier memperingatkan bahwa pergeseran seperti ini justru akan memicu kemerosotan ekonomi, karena sumber daya dialihkan dari investasi produktif—seperti pendidikan atau infrastruktur—ke upaya mempertahankan kekuasaan sehingga justru menciptakan inefisiensi.
Inefisiensi yang mungkin terjadi, sebagaimana kita pahami bahwa militer dilatih untuk pertahanan bukan administrasi, dan sangat mungkin tak punya keahlian untuk jabatan sipil. Chain of command militer, komando militer dalam suatu bidang sipil yang dijabat militer aktif akan menjadi ambigu sehingga justru menurunkan efisiensi dalam tugas sipil.
Meizner (2020) menyoroti bagaimana pejabat militer era Soeharto sering mengutamakan loyalitas ketimbang kompetensi, pola yang bisa muncul kembali. Di tengah deflasi, ketika alokasi sumber daya yang efisien sangat krusial, ini bisa memperburuk masalah ekonomi dimana alih-alih berfokus pada kesejahteraan, peran militer dalam sipil akan lebih mengutamakan kontrol ketimbang pembangunan.
Jika hal tersebut berlanjut, kepercayaan investor juga jadi korban. Indonesia bergantung pada modal asing untuk pertumbuhan, tapi persepsi kembalinya otoritarianisme bisa memicu pelarian modal atau meningkatkan terjadinya rent seeking, memaksa peningkatan penghematan. Rent seeking yang tidak terkendali ini tidak akan menjamin keamanan investasi dengan jaminan hak properti dan mengurangi korupsi—kualitas yang terancam oleh ekspansi militer di ruang sipil.
Sejarah militer dalam bisnis buram dan praktik rente di masa lalu juga menunjukkan potensi penyalahgunaan saat RUU ini diterapkan. Dana publik berisiko disalahgunakan, melemahkan integritas institusi. Jeffrey Winters dalam Oligarchy (2011) berpendapat bahwa sistem politik Indonesia didominasi elit oligarki yang memanipulasi institusi untuk keuntungan pribadi.
UU ini bisa memperkuat oligarki itu dengan menyatukan kepentingan militer dan bisnis, memperdalam ketimpangan dan membatasi mobilitas ekonomi—tantangan yang sudah memburuk akibat deflasi, pengangguran dan penghematan yang terjadi.
Penutup
Sebagai penyikapan atas disahkannya RUU TNI ini, kita perlu menatap masa depan serta belajar dari masa lalu, dimana militer menawarkan stabilitas sementara dengan mengorbankan masa depan. Mengandalkan militer untuk mengatasi pengangguran, penghematan, dan deflasi berarti mengabaikan solusi berkelanjutan seperti investasi pada lapangan kerja, jaminan sosial serta kesejahteraan.
Jalan terbaik ke depan adalah memperkuat institusi demokratis. Bahwa partisipasi publik adalah pilar demokrasi Indonesia, meski tidak sempurna. Militerisasi berpotensi menekan partisipasi ini, merusak tata kelola yang responsif. Pengawasan publik dan penolakan terhadap RUU ini krusial untuk menjaga ide dan ruh reformasi 1998 serta memastikan kemakmuran jangka panjang Indonesia.
*) Faith Liberta Aieda merupakan Mahasiswa Magister Antropologi UGM, peneliti Ekonomi dan Ekologi-Politik. di Srawungpedia
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
Naskah dikirim ke alamat email [email protected].
Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
Panjang naskah maksimal 800 kat
a
Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
Hak muat redaksi.(*)