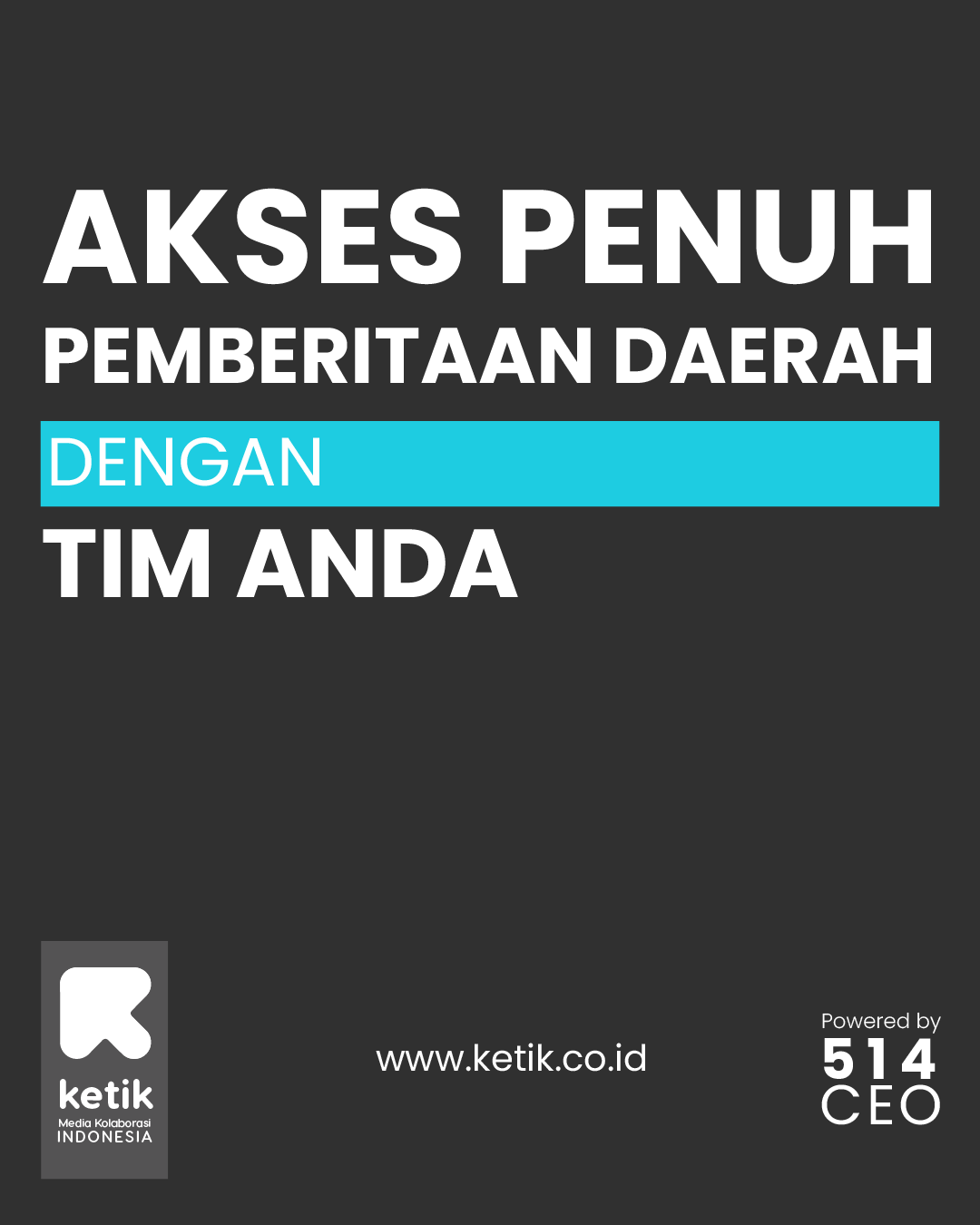Setiap menjelang hari raya, baik Idulfitri maupun Natal, toples-toples kue mulai berjajar rapi di ruang tamu. Di antara deretan kue kering itu, ada satu yang hampir selalu hadir dan menjadi primadona: nastar.
Kue mungil berbentuk bulat dengan isian selai nanas ini seolah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan hari besar di Indonesia. Rasanya yang manis dan sedikit masam, berpadu dengan aroma butter yang gurih, menjadikan nastar bukan sekadar camilan, melainkan simbol kebersamaan dan perayaan.
Meski sangat identik dengan momen-momen istimewa di Tanah Air, nastar sebenarnya bukan kue asli Indonesia. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga ke negeri Belanda. Nama “nastar” sendiri berasal dari bahasa Belanda: “ananas” yang berarti nanas, dan “taart” yang berarti tart atau pie.
Seiring waktu dan pelafalan orang Indonesia, “ananas taart” berubah menjadi “nastar”, kue tart berisi selai nanas. Dalam bahasa Inggris, kue ini dikenal sebagai pineapple tart atau pineapple nastar roll.
Namun, seberapa banyak pun nama dan variasinya, bagi masyarakat Indonesia, nastar tetaplah nastar: kue kering manis dengan cita rasa yang membangkitkan kenangan. Awal mula nastar hadir di Indonesia adalah bagian dari kisah panjang kolonialisme Belanda di Nusantara.
Pada masa Hindia Belanda, membawa serta budaya dan kebiasaan mereka, termasuk dalam hal makanan. Tart buah adalah salah satu kudapan khas Eropa yang sering hadir dalam tradisi Natal orang-orang Belanda. Biasanya tart tersebut berisi buah seperti apel, stroberi, atau blueberry.
Namun, ketika berada di Indonesia, buah-buahan tersebut sulit ditemukan karena iklim tropis. Sebagai gantinya, nanas yang melimpah di tanah Nusantara dipilih sebagai bahan isian, dan terciptalah selai nanas sebagai elemen utama dari nastar.
Dikutip dari buku Ragam Kudapan Jawa karya Murdijati-Gardjito dan kawan-kawan (2023), pada masa kolonial, nastar termasuk kudapan mewah. Mentega dan tepung terigu yang menjadi bahan utamanya merupakan barang impor, sehingga hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan, baik Belanda maupun priyayi pribumi.
Biasanya, orang-orang Belanda membuat kue ini untuk perayaan Natal mereka. Namun, ketika menjalin relasi dengan bangsawan lokal, mereka kerap mengirim hantaran kue, termasuk nastar, saat momen lebaran.
Dari sinilah kebiasaan menghadirkan nastar saat Idulfitri mulai berkembang di kalangan pribumi, meski awalnya hanya terbatas pada mereka yang memiliki akses terhadap bahan dan pengetahuan kuliner ala Eropa.
Seiring berjalannya waktu dan semakin mudahnya memperoleh bahan-bahan seperti mentega dan tepung, nastar mulai dikenal luas di berbagai lapisan masyarakat.
Kue ini kemudian mengalami proses adaptasi dan akulturasi, yaitu penggabungan unsur budaya asing dan lokal. Nastar yang semula hanya ada di meja makan para bangsawan, kini menjadi sajian wajib hampir di setiap rumah saat lebaran tiba.
Tradisi menyajikan nastar pun melekat dalam budaya masyarakat, bahkan hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Di sana, nastar dikenal dengan berbagai nama dan bentuk, namun tetap mempertahankan cita rasa khasnya: manis, asam, dan gurih, dengan tekstur lembut yang mudah lumer di mulut.
Dilansir dari Kompas.com, menurut sejarawan kuliner dari Universitas Padjadjaran, Fadly Rahman, kebiasaan membuat dan menyajikan kue kering seperti nastar di Indonesia baru berkembang setelah masyarakat mengenal tradisi kuliner Belanda.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana kolonialisme tak hanya berdampak pada politik dan ekonomi, tetapi juga pada kebiasaan sehari-hari, termasuk makanan. Nastar menjadi contoh nyata bagaimana sesuatu yang awalnya asing bisa menjadi bagian penting dari identitas budaya lokal melalui proses adaptasi yang berlangsung secara alami.
Kini, nastar hadir tak hanya dalam bentuk klasik, tapi juga dengan berbagai inovasi. Ada yang menambahkan keju di adonan, menciptakan rasa gurih yang lebih kuat. Ada pula yang membuat bentuk nastar menyerupai buah nanas kecil, lengkap dengan corak dan warna yang menyerupai kulit nanas.
Meskipun demikian, ciri khasnya sebagai kue kering berisi selai nanas tetap dipertahankan. Inovasi ini menjadi bukti bahwa nastar terus berevolusi sesuai selera zaman, tanpa meninggalkan akar sejarahnya.
Kehadiran nastar dalam setiap perayaan bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang tradisi dan kenangan. Aroma butter yang menyeruak saat toples dibuka, rasa manis dan sedikit asam dari selai nanas, serta tekstur lembut yang meleleh di mulut seolah membawa kita kembali ke masa kecil, saat berkumpul bersama keluarga dan kerabat.
Nastar telah menjadi bagian dari cerita hidup banyak orang Indonesia, dari generasi ke generasi. Nastar juga mencerminkan bagaimana identitas budaya terbentuk dan berkembang. Ia bukan sekadar produk kolonial, tapi juga hasil dari kreativitas masyarakat yang mampu mengolah, menyesuaikan, dan menjadikannya bagian dari budaya lokal.
Kue ini menjadi simbol akulturasi yang harmonis, di mana warisan kolonial diolah sedemikian rupa hingga memiliki nilai dan makna baru dalam konteks budaya Indonesia.
Dalam setiap gigitan nastar, tersimpan jejak sejarah panjang interaksi antara budaya Barat dan Timur. Nastar adalah bukti bahwa makanan bisa menjadi jembatan budaya, penghubung antara masa lalu dan masa kini.
Dari meja makan bangsawan Belanda hingga ruang tamu rumah-rumah sederhana di Indonesia, nastar telah menempuh perjalanan panjang, dan kini menetap sebagai bagian dari identitas kuliner Nusantara.
Maka tidak berlebihan jika kita menyebut nastar sebagai kue lebaran beraroma colonial kue kecil dengan cerita besar, yang terus hadir dari waktu ke waktu, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan budaya masyarakat Indonesia.
*) Agus Mahfudin Setiawan merupakan Dosen Sejarah dan Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email [email protected].
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakanidentitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)