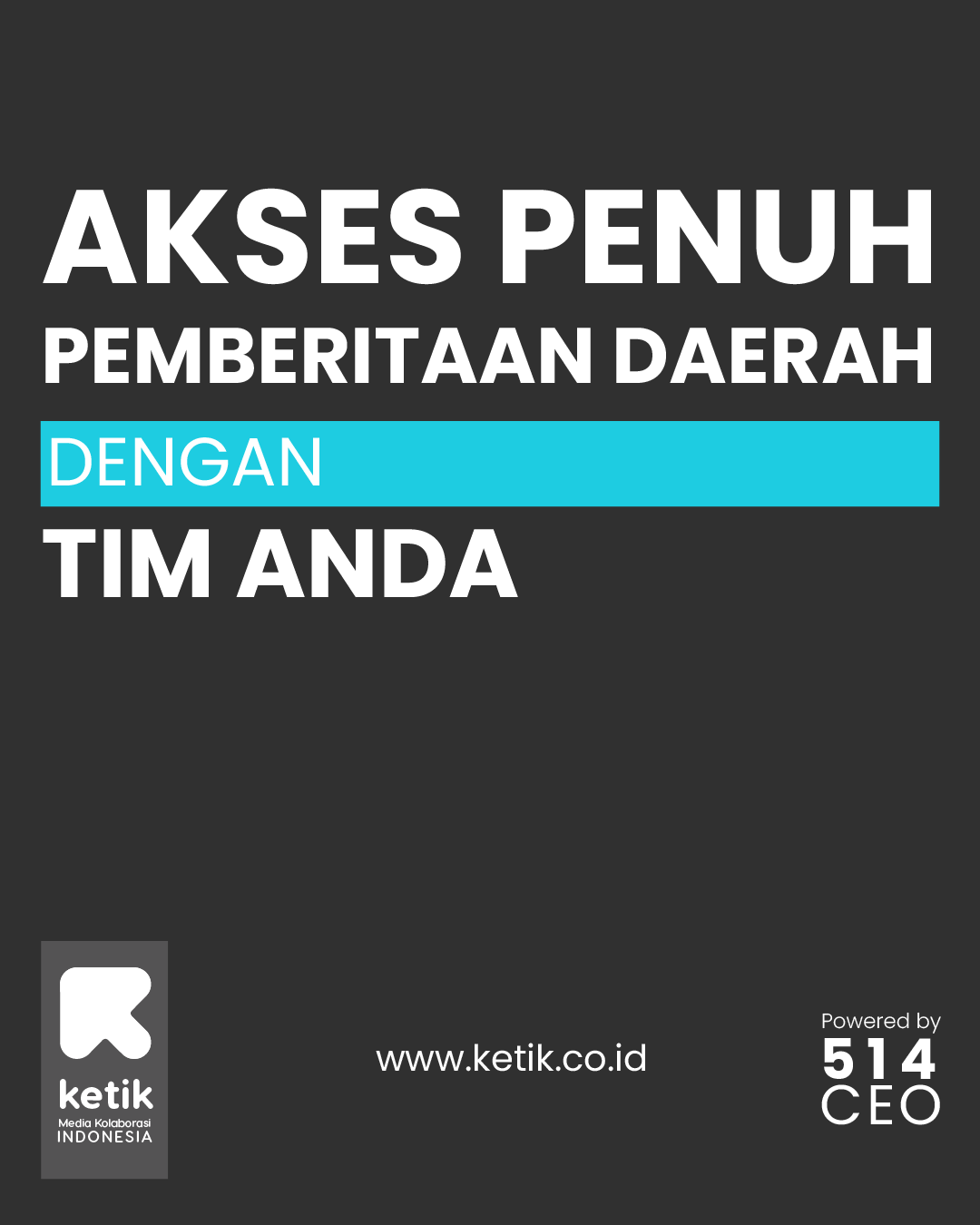Dalam gelombang perubahan yang terus mengalir, setiap bangsa diuji dengan tantangan yang kian kompleks. Indonesia, sebagai negara yang tumbuh dari semangat perjuangan, kini dihadapkan dinamika baru. Dinamika yang menuntut adaptasi tanpa kehilangan jati diri.
Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru disahkan salah satu cerminan dari tantangan tersebut. Di satu sisi, sebuah upaya menyesuaikan peran militer dengan realitas zaman. Sisi lainnya, sekaligus menyalakan percikan kontroversi yang membelah pandangan publik.
Penulis yakin semua orang tahu, dunia telah berubah. Perang tak lagi hanya soal pertempuran di garis depan. Tetapi juga menyusup dalam wujud ancaman siber, infiltrasi ideologi radikal, serta intervensi geopolitik. Aktivitas tersebut bergerak tanpa perlu mengirimkan pasukan.
Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, dan Tiongkok, telah lama memperluas peran militer mereka untuk menghadapi ancaman non konvensional ini. Maka, ketika Indonesia, mencoba menyesuaikan langkah dengan realitas yang ada, tidakkah itu menjadi suatu keniscayaan?
Namun, perubahan selalu datang dengan kekhawatiran. Kritik terhadap revisi UU TNI berakar dari ingatan kolektif bangsa terhadap masa lalu. Ketika militer bukan hanya penjaga pertahanan. Tetapi juga tangan kekuasaan yang mencengkeram berbagai aspek kehidupan sipil.
Trauma akan dwifungsi ABRI masih membayang, menimbulkan pertanyaan apakah revisi ini adalah langkah maju. Atau justru pintu belakang yang membawa kita kembali ke era yang telah ditinggalkan? Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Sebab sejarah telah mengajarkan bahwa kekuatan tanpa kontrol, jelas menjadi ancaman bagi demokrasi.
Salah satu pasal yang paling menuai kontroversi adalah peluang bagi prajurit aktif menduduki jabatan sipil. Baik di kementerian maupun lembaga negara. Bagi sebagian kalangan, hal ini dianggap sebagai kemunduran, bahkan berpotensi mengikis supremasi sipil. Namun, jika ditelaah lebih dalam, kehadiran militer dalam jabatan sipil bukanlah hal asing.
Di banyak negara demokratis, mantan perwira militer seringkali diberi kepercayaan memimpin kementerian strategis. Khususnya yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Di Indonesia sendiri, tokoh seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Moeldoko, dan Prabowo Subianto, adalah contoh bagaimana perwira militer dapat bertransformasi menjadi pejabat publik tanpa merusak sistem demokrasi.
Yang seharusnya menjadi perhatian utama bukanlah ada atau tidaknya militer di ranah sipil. Tetapi bagaimana mekanisme kontrolnya diterapkan. Jika terdapat sistem checks and balances yang ketat, di mana TNI tetap berada di bawah kendali sipil, maka kekhawatiran kembalinya dwifungsi dapat diminimalisasi.
Sebaliknya, jika pengawasan terhadap peran TNI dalam jabatan sipil lemah, maka kritik yang disuarakan menjadi sesuatu yang harus didengar dan ditindaklanjuti.
Lebih jauh, penolakan terhadap revisi UU TNI juga mencerminkan ketegangan lama antara militer dan birokrasi sipil. Banyak yang beranggapan, kehadiran prajurit dalam jabatan sipil akan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Persaingan militer dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kekhawatiran ini tentu beralasan, mengingat banyaknya lulusan sekolah tinggi pemerintahan dan akademi sipil yang telah lama berjuang dalam sistem birokrasi. Namun, di sisi lain, pengalaman dan disiplin militer dapat menjadi elemen yang mempercepat reformasi birokrasi yang selama ini dikenal lambat dan penuh hambatan.
Sejarah mencatat, TNI bukanlah entitas asing bagi masyarakat sipil. Selama bertahun-tahun, militer telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak hanya dalam konteks pertahanan, tetapi juga dalam misi sosial.
Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), misalnya. Adalah bukti nyata bagaimana TNI terlibat dalam pembangunan infrastruktur desa. Membuka akses jalan di wilayah terpencil. Hingga membantu rehabilitasi sekolah dan rumah ibadah. Begitu pula dengan keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana. Di mana prajurit turun langsung dalam evakuasi korban, distribusi logistik, serta pemulihan daerah terdampak.
Dalam pandemi COVID-19, TNI juga memainkan peran vital dalam distribusi vaksin. Pengawasan protokol kesehatan, serta penyediaan fasilitas kesehatan darurat. Keberadaan mereka di tengah masyarakat telah menjadi bagian dari upaya negara dalam menghadapi krisis.
Oleh karena itu, memperdebatkan peran TNI dalam ranah sipil seharusnya tidak hanya berkutat pada kekhawatiran akan militerisasi pemerintahan. Tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang bisa ditawarkan. Selama ada mekanisme pengawasan yang jelas dan transparan, kenapa kekhawatiran harus dinarasikan berjilid-jilid.
Pada akhirnya, demokrasi tidak boleh didefinisikan sebagai penolakan terhadap militer dalam kehidupan sipil. Tetapi sebagai upaya membangun sistem yang mampu mengontrol setiap elemen kekuasaan agar tetap berada dalam jalur yang benar. Sejarah juga mencatat kekuatan militer yang tidak dikendalikan dapat menjadi ancaman. Tetapi ia juga mencatat bahwa negara yang lemah dalam menghadapi ancaman keamanan akan mudah terguncang.
Alih-alih menolak secara mutlak atau menerima tanpa kritik, yang lebih dibutuhkan adalah dialog yang terbuka dan konstruktif. Jika revisi UU TNI memiliki celah yang dapat disalahgunakan, maka yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasannya.
Bukan menutup diri dari segala bentuk perubahan. Sebab, dalam setiap langkah yang diambil, sejarah akan mengingat bukan hanya tentang siapa yang menang dalam perdebatan. Tetapi bagaimana sebuah bangsa mengelola perbedaannya demi menjaga keseimbangan antara demokrasi, keamanan, dan kemajuan.
*) Eko Hardianto merupakan Jurnalis Ketik.co.id yang bertugas di Probolinggo
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email [email protected].
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)